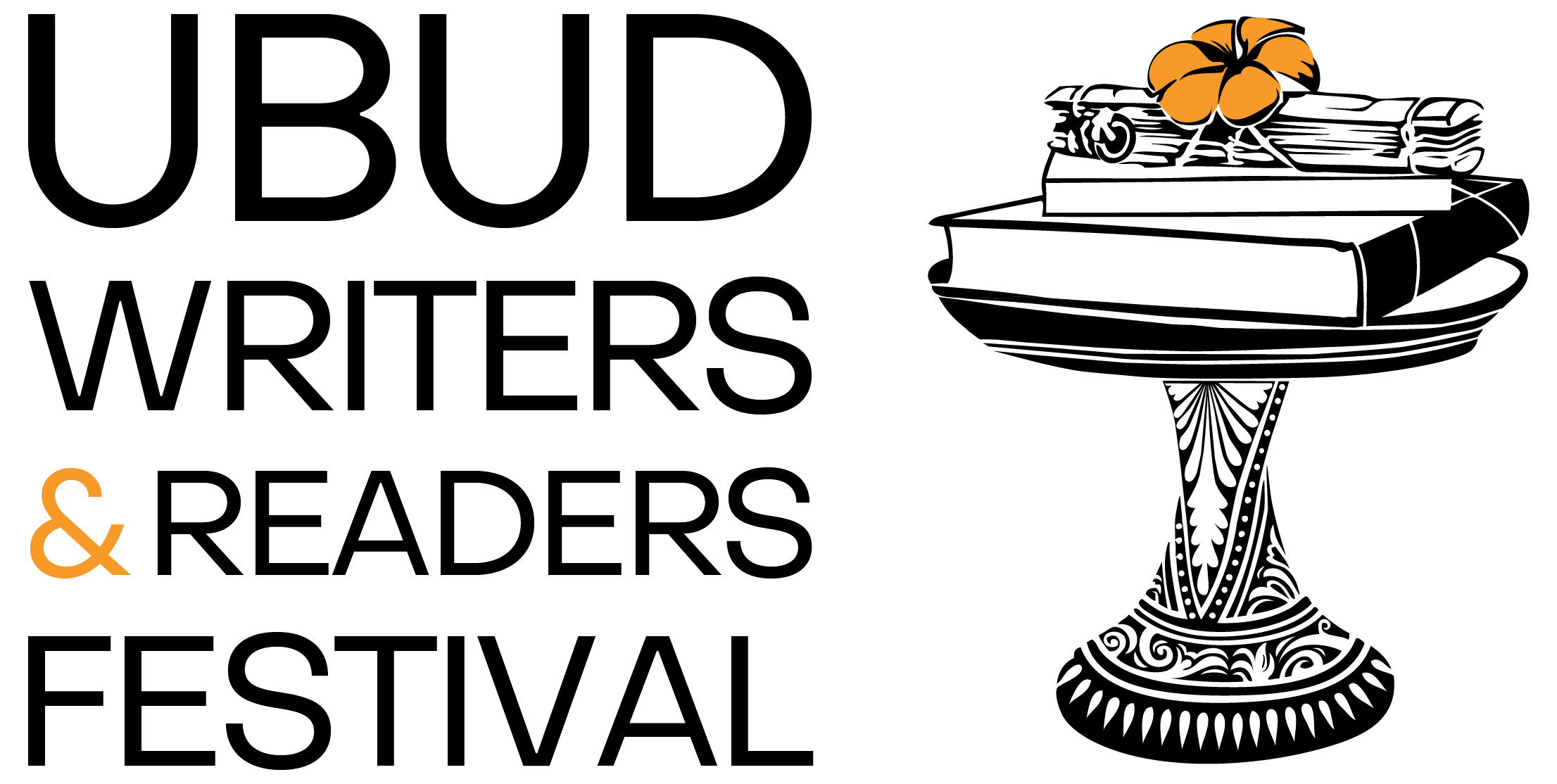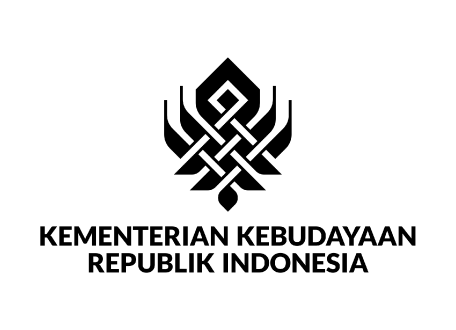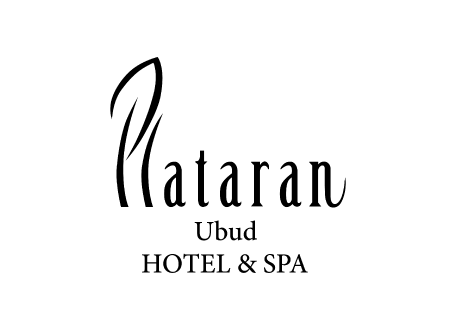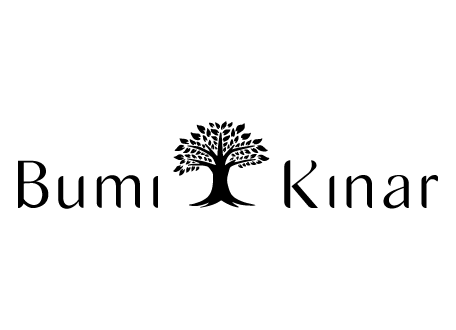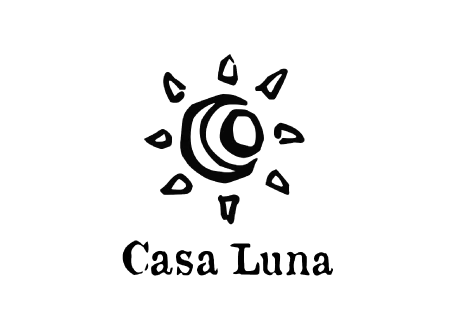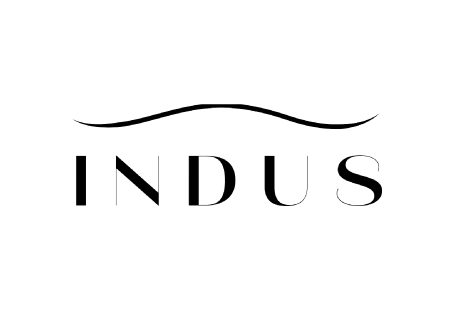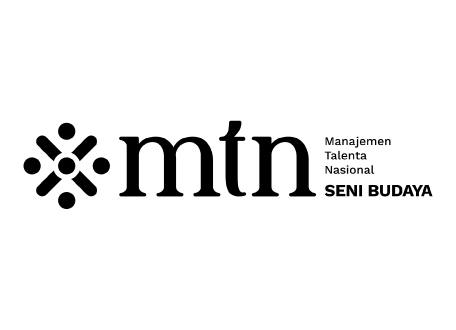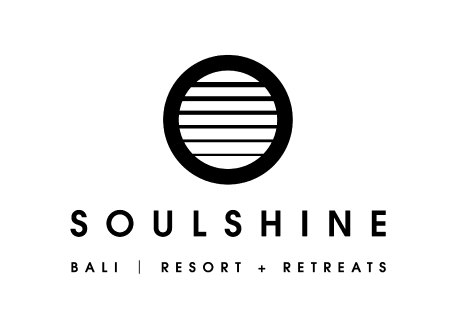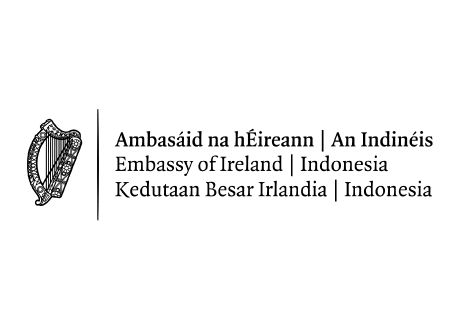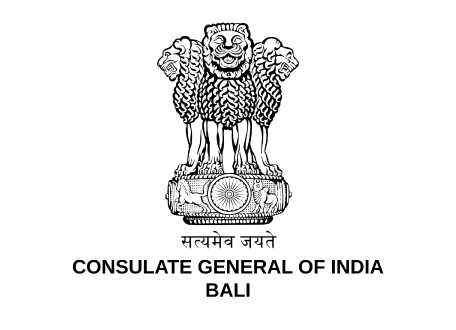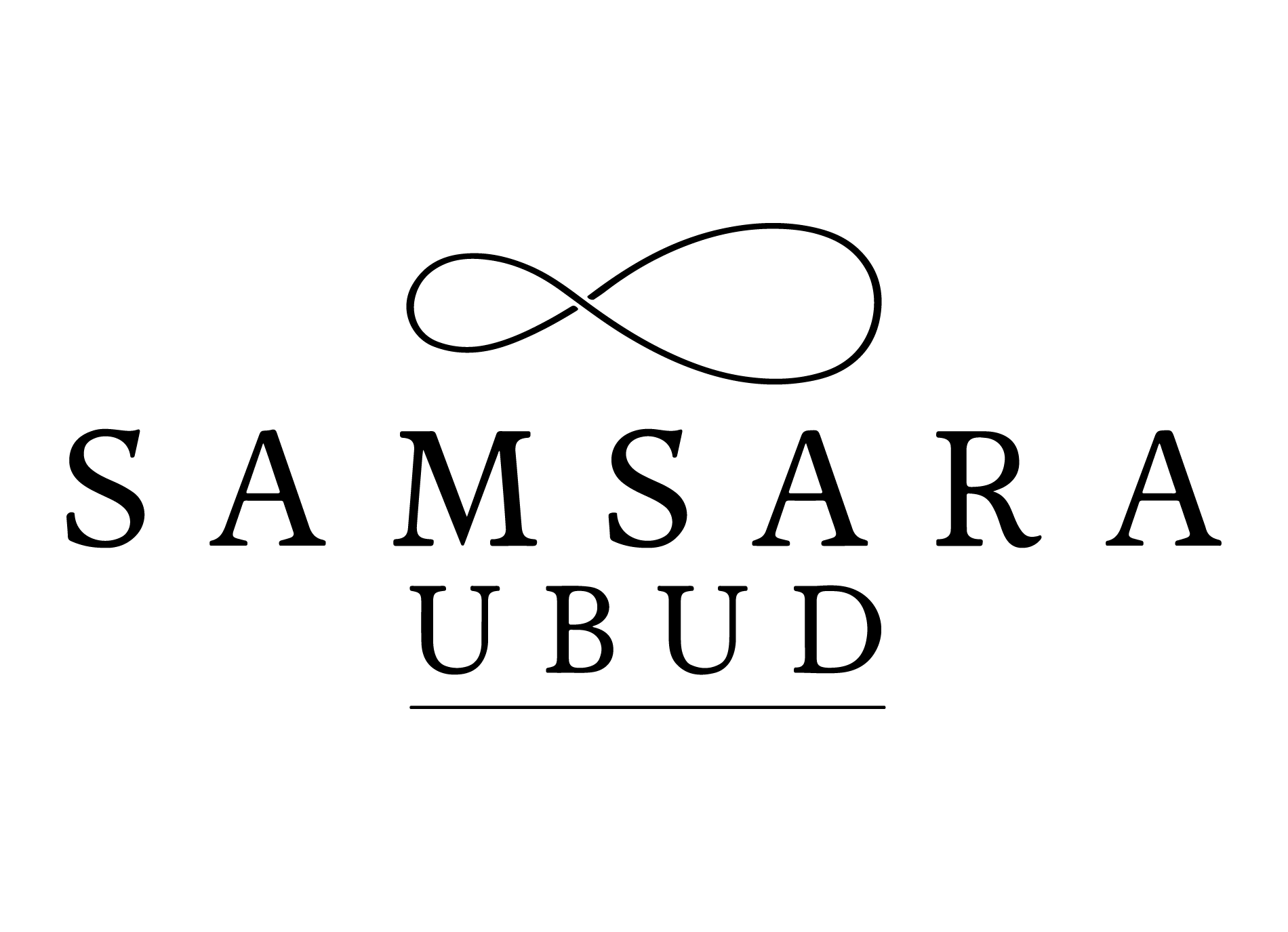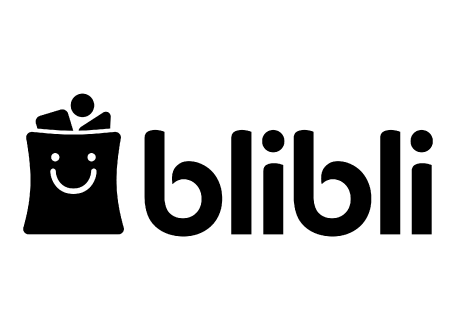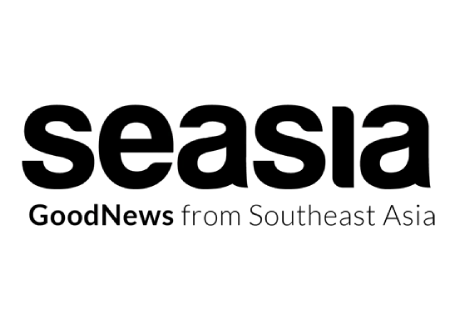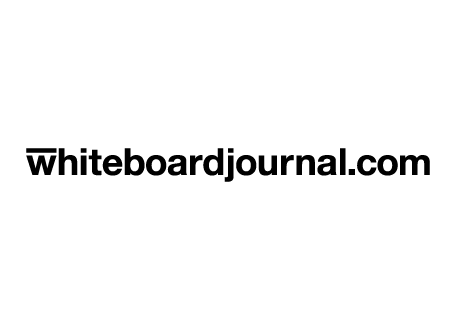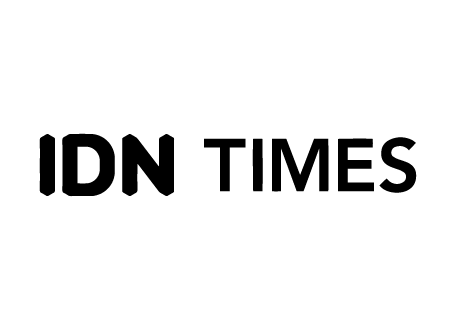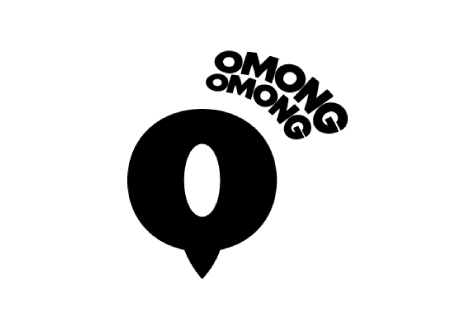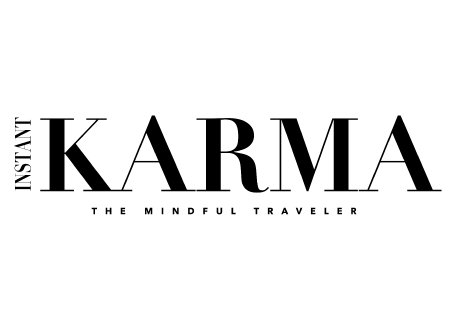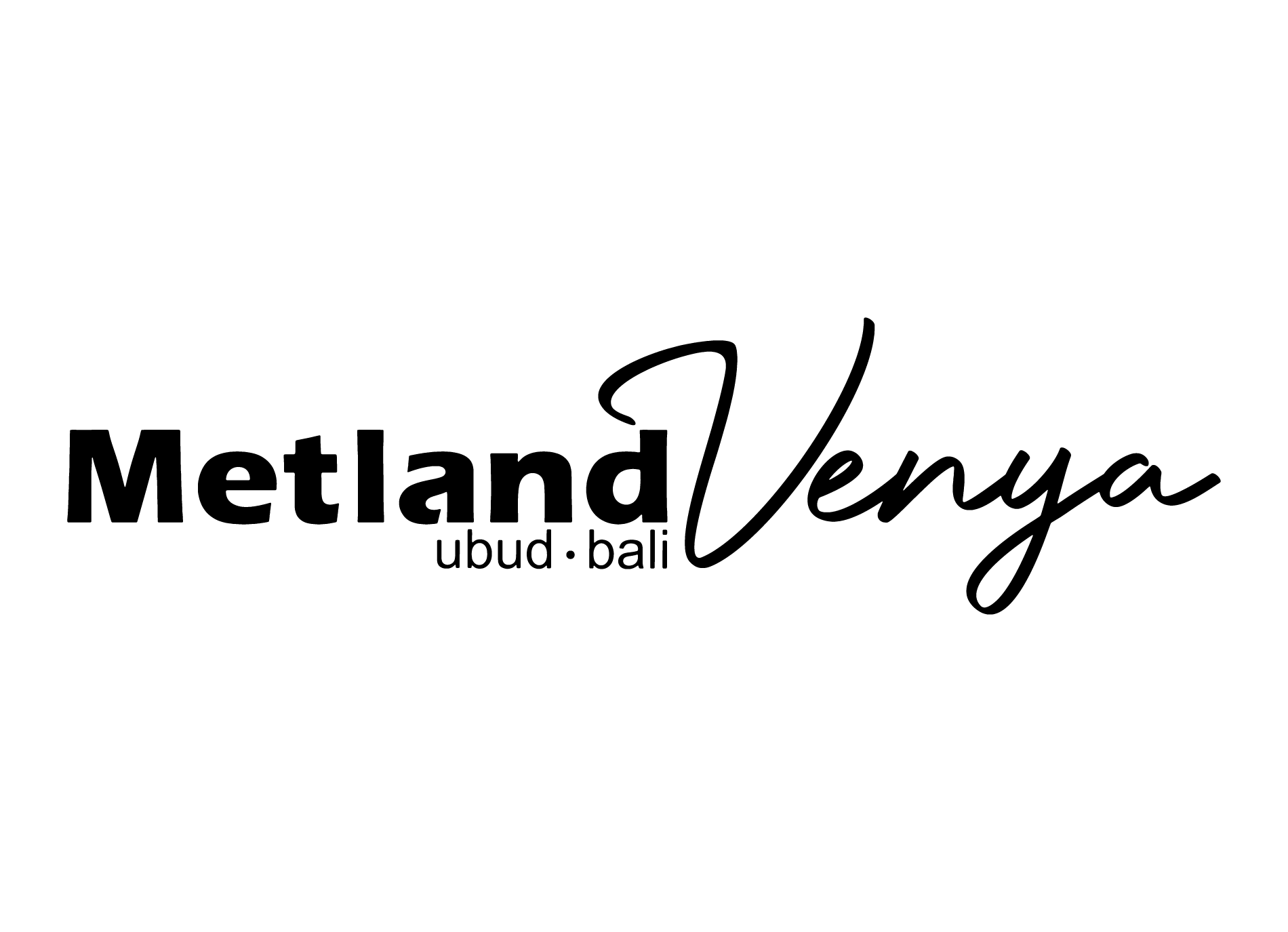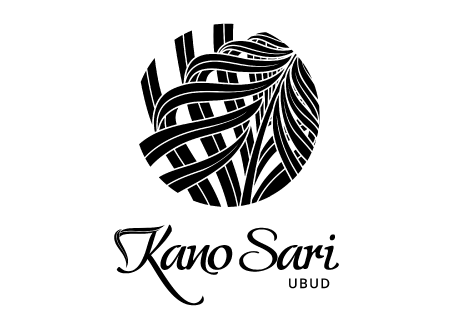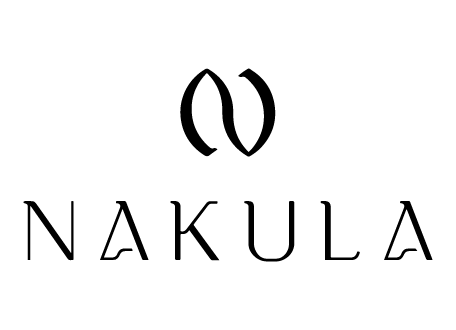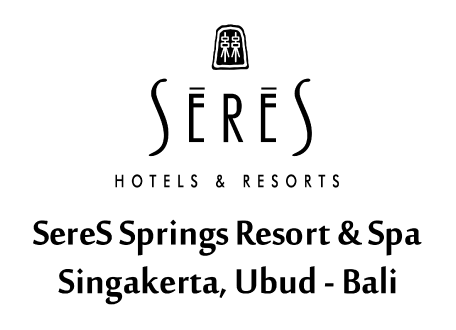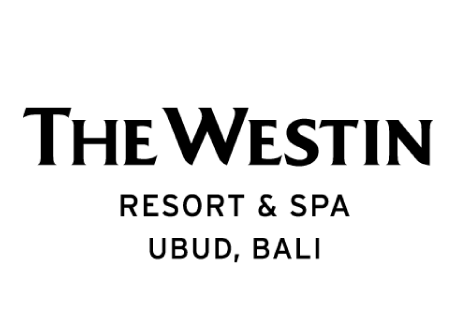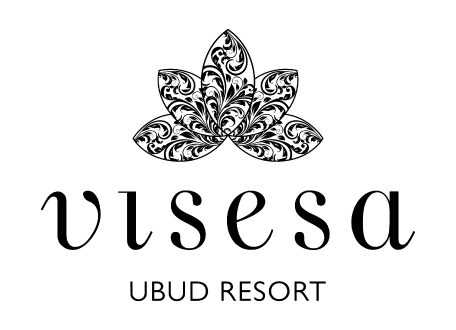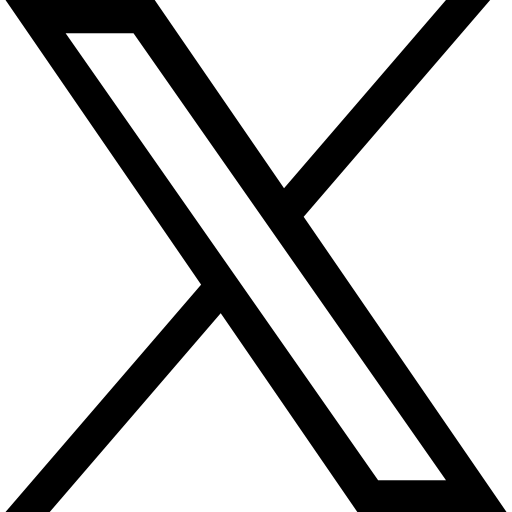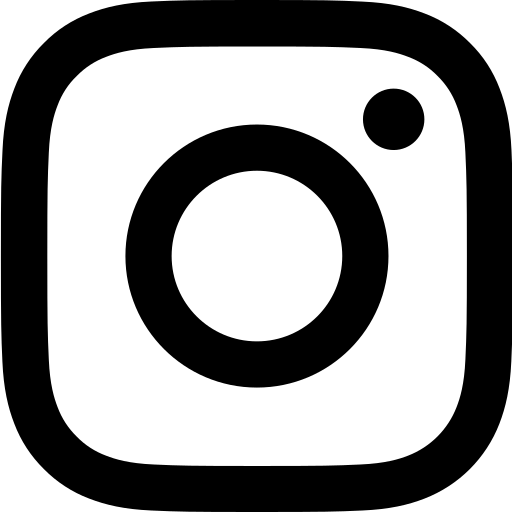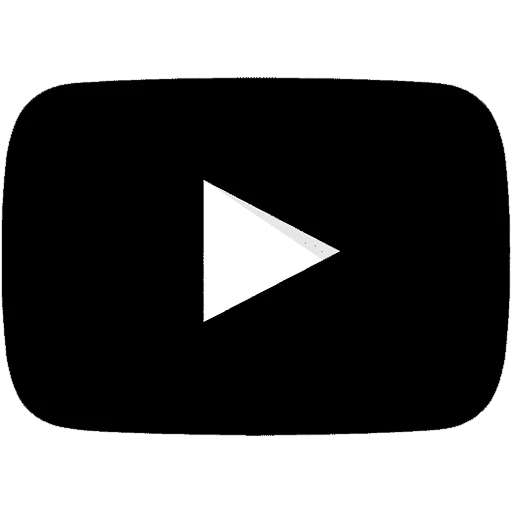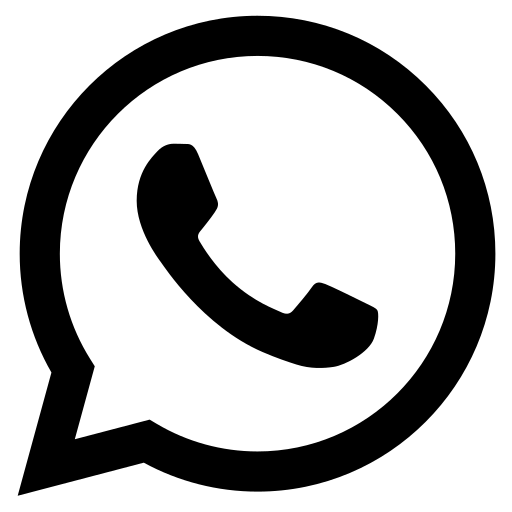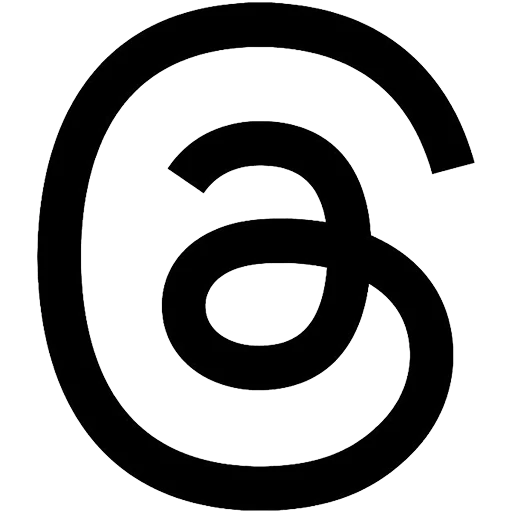Seleksi penulis pemula (emerging writers) UWRF merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Yayasan Mudra Swari Saraswati sejak 2008 sebagai upaya untuk memetakan, merangkul, dan memberi ruang publikasi kepada emerging writers di seluruh Indonesia. Sesuai ketentuan seleksi tahun 2026, emerging writers diminta untuk mengirimkan satu cerita pendek (cerpen), dengan melampirkan karya-karya lainnya sebagai bahan pertimbangan.
Bagi emerging writers, cerpen bukan sekadar bentuk yang lebih singkat daripada novel. Ia adalah laboratorium kepengarangan yang sesungguhnya. Di ruang yang serba terbatas, setiap pilihan etis dan estetis terkait isi dan komposisi memikul beban yang jauh lebih berat. Cerpen yang kuat adalah demonstrasi dari kemahiran artistik dan ketajaman visi. Ia menguji kemampuan penulis untuk menciptakan dunia yang utuh dan menghunjam dalam ruang minimal, sekaligus memicu resonansi yang berdenyut lama setelah pembacaan usai. Seleksi emerging writers UWRF, dengan demikian, tidak semata mencari “cerita yang bagus”, tetapi juga upaya untuk mengenali benih suara khas (authorial voice), menguji ketajaman sebuah pandangan dunia, dan menemukan potensi sebuah karier kepenulisan yang cemerlang.
Untuk mencapai tujuan itu, proses kurasi dilakukan dalam dua modus sekaligus: membaca vertikal dan membaca horizontal. Membaca vertikal adalah telaah mendalam atas masing-masing naskah untuk menemukan keunikan, keutuhan, dan keunggulan teksnya. Membaca horizontal adalah upaya untuk menangkap pola-pola tertentu yang muncul dari keseluruhan naskah peserta, baik dalam aspek kecenderungan tematik hingga eksperimen bentuk. Pemetaan ini, tentu saja, bukan untuk menyamaratakan atau memilah sekelompok naskah dalam kotak atau kategori tertentu, tetapi justru untuk memberi konteks pada setiap karya. Sebuah cerpen menjadi lebih menarik ketika ia dapat berdialog dengan tren yang ada, baik dengan menguatkannya, mengkritisinya, atau menawarkan jalan keluar yang sama sekali berbeda. Selain itu, dengan pandangan meluas semacam ini, kami dapat meletakkan berbagai pokok soal yang digarap para penulis dengan ukuran-ukuran keunggulan yang lebih inklusif. Semua tema setara, tak ada hierarki. Tema-tema politik, misalnya, tidak lebih penting daripada tema-tema domestik.
Melalui pembacaan berlapis, yang bergerak ulang-alik dalam dua modus tersebut, kami dapat menguji pertaruhan teknik dan gagasan yang ditawarkan setiap penulis, sembari mengamati apakah keduanya saling terjalin dan memperkuat atau justru berlepasan. Sesuai kelaziman, parameter teknis yang dipakai untuk menilai setiap naskah yang masuk mencakup:
- Ekonomi Narasi (Apakah penulis mampu menciptakan densitas dan keutuhan dalam ruang yang pendek? Apakah setiap elemen naratif berfungsi dan bekerja secara efisien untuk membangun efek yang diinginkan?).
- Suara dan Sudut Pandang (Apakah pilihan sudut pandang disengaja dan dipertahankan untuk menciptakan koherensi dunia cerita? Apakah terdengar suara khas, yang timbul dari kombinasi persona narator, pilihan detail, dan sikap terhadap dunia dalam cerita? Apakah pengolahan bahasa dikerjakan secara serius, sehingga diksi dan ritme kalimat mendukung suara khas tersebut?).
- Struktur dan Bentuk Inovatif (Apakah penulis berani memainkan struktur atau bermain dengan bentuk, tanpa terbaca hanya sebagai gimik?).
- Perwujudan Gagasan (Apakah tema yang digarap berhasil dileburkan dalam elemen-elemen naratif, misalnya dalam adegan, penokohan, atau dialog, alih-alih diwartakan melulu sebagai wacana?).
Naskah cerpen yang diikutsertakan dalam seleksi datang dari 634 penulis, terdiri dari 367 penulis perempuan, 256 penulis laki-laki, dan 11 penulis yang memilih untuk tidak menyebutkan identitas gendernya. Terkait aspek geografis, peserta seleksi berasal dari berbagai penjuru Indonesia, dari Aceh sampai Papua, meskipun sebarannya tidak merata. Pulau Jawa masih mendominasi, dengan total penulis sejumlah 413 orang, terbanyak dari Jawa Barat (126 penulis) dan paling sedikit dari Banten (18 penulis). Partisipasi penulis dari Pulau Sulawesi dan Pulau Sumatra relatif berimbang. Dari Pulau Sulawesi, terbanyak dari Sulawesi Utara (25 penulis) dan paling sedikit dari Sulawesi Tenggara (1 penulis), sementara dari Pulau Sumatra, terbanyak dari Riau (19 penulis) dan paling sedikit dari Bangka Belitung (1 penulis). Dari Pulau Kalimantan, terbanyak dari Kalimantan Selatan (11 penulis) dan paling sedikit dari Kalimantan Utara (1 penulis). Bali, NTT, NTB, Papua, dan Maluku berturut-turut menyumbangkan 40, 8, 6, 6, dan 3 penulis. Data tersebut menunjukkan bahwa antusiasme penulis pada seleksi emerging writers UWRF sangatlah besar, meskipun partisipasi per wilayah masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Kabar baiknya, ketimpangan partisipasi itu tentu saja tidak mengurangi peluang seorang penulis untuk terpilih. Peluang seorang penulis untuk terpilih pada dasarnya adalah 1/634, tidak peduli apakah ia satu-satunya penulis dari Kalimantan Utara, atau satu dari 126 penulis yang berasal dari Jawa Barat.
Terlepas dari urusan statistik, naskah-naskah yang menonjol pada akhirnya adalah cerpen yang tidak hanya memenuhi parameter teknis dengan baik, tetapi juga berani mengambil risiko. Risiko dalam eksperimentasi bentuk, risiko dalam menyelami gagasan yang kompleks dan subtil, atau risiko dalam memilih sudut pandang yang tidak biasa seringkali menjadi faktor pembeda antara cerpen yang “sekadar” bagus dan cerpen yang beresonansi—yang meninggalkan jejak dalam pikiran dan perasaan, serta membuka kemungkinan untuk dibaca dan ditafsir ulang.
Pokok soal yang dikisahkan dalam cerpen-cerpen yang masuk dalam seleksi emerging writers sangat bervariasi. Namun, secara tematik, tren dominan yang tampak kentara adalah sebagai berikut:
Pertama, isu lingkungan, perebutan ruang, dan bencana ekologis, baik yang secara terang benderang menghamparkan masalah ketimpangan kuasa antara negara/korporasi dan masyarakat korban perampasan lahan atau secara filosofis mempersoalkan hubungan manusia dan alam, yang sebagian besarnya berisi gugatan pada keserakahan manusia dalam mengeksploitasi alam. Persoalannya, cukup banyak cerpen yang tergelincir menjadi pamflet, dengan mengulang-ulang narasi heroik perlawanan yang simplistik.
Kedua, tema trauma yang tak selesai, baik yang dialami individu dalam latar dinamika keluarga atau trauma kolektif yang diwarisi akibat kekerasan sruktural dan kultural dalam latar negara-bangsa. Pertanyaan yang bisa diajukan untuk mengukur kekuatan cerpen dengan tema ini adalah apakah dalam semesta cerita, penulis sebatas melukiskan luka dan kekerasan, atau mampu menyingkap lapis-lapis sejarah, penyebab, dan dampaknya? Di mana letak agensi sang korban? Apakah mereka hanya pasif menderita, atau terdapat upaya, sekecil apa pun, untuk mengartikulasikan, mengarsipkan, atau mengubah narasi traumanya, meski hanya untuk dirinya sendiri?
Ketiga, tema lokalitas dan tegangan identitas terkait adat-tradisi. Sebagian cerpen masih terjebak menjadi semacam katalog budaya yang eksotis atau slogan klise tentang “kearifan lokal”. Sebagian lain berhasil mentransformasikan bahan budaya menjadi kisah yang tidak hanya bercerita tentang adat, tetapi menggunakan logika, metafora, dan konflik dari dunia adat tersebut untuk menawarkan semacam peta makna alternatif di tengah arus global yang homogen. Karya-karya semacam ini berhasil menjadi jendela sekaligus cermin: jendela untuk melihat ke dalam suatu dunia yang spesifik, dan cermin untuk melihat refleksi kecemasan, pergulatan, dan pertanyaan eksistensial manusia modern, di mana pun kita berada.
Keempat, tema perempuan, yang mempersoalkan agensi, trauma, otonomi tubuh, seksualitas, dan seterusnya, dalam latar tradisi atau masyarakat urban. Cerpen-cerpen bertema perempuan yang kurang mengesankan umumnya terjebak pada wacana permukaan, atau justru terlampau berat menggendong wacana sehingga penyajian kisah seolah terabaikan. Cerpen-cerpen yang menarik, sebaliknya, lancar bertutur tentang perempuan-perempuan yang berada di persimpangan antara tuntutan adat, tekanan sistem patriarki, dan kerinduan akan otonomi diri. Poin penting yang bisa disoroti dari kisah-kisah tersebut adalah bagaimana agensi perempuan muncul justru melalui penguasaan dan transformasi kode kulturalnya sendiri.
Kelima, tema masyarakat urban dan kehidupan digital, dengan segala permasalahan khas seperti alienasi, disrupsi teknologi, relasi antarmanusia atau relasi antara manusia dan mesin di era media sosial, dan sebagainya. Tema urban-digital ini menarik karena sering dianggap “mudah” tetapi justru rentan menjadi klise. Cerpen-cerpen yang kuat mesti melampaui deskripsi permukaan tentang, misalnya, “kesepian di kota besar” atau “kecanduan media sosial” atau “manusia versus mesin”, tetapi berhasil menangkap logika eksistensial dan relasional baru yang lahir dari kondisi paradoks era hiperkoneksi.
Seleksi emerging writers 2026 berlangsung dalam dua tahap, yakni pre-kurasi oleh A. Nabil Wibisana dan Siska Yuanita, dengan membaca keseluruhan naskah masuk untuk memilih 50 cerpen yang layak bersaing ke tahap berikutnya. Kandidat yang lolos pada tahap pre-kurasi ternyata melebihi rencana awal karena cukup banyak cerpen dinilai memiliki kualitas sebanding. Seleksi tahap akhir, dilakukan bersama Cyntha Hariadi, yang membaca 70 cerpen lolos pre-kurasi. Kami bertiga membaca naskah, menimbang kekuatan dan kelemahannya, dan memutuskan emerging writers terpilih di pekan-pekan sebelum dan setelah pergantian tahun.
“Tahun 2025 adalah tahun penuh prahara bagi negara kita; kita menutupnya dengan kemarahan, kesedihan, dan keputusasaan. Namun membuka mata di tahun 2026—sebagai manusia, mau tak mau kita mesti memilih hidup. Salah satu cara bertahan adalah melakukan refleksi atas kemanusiaan kita. Dalam karya sastra, tindakan ini tercermin dalam tema yang relevan dan dekat serta kekriyaan yang rata-rata cukup baik, bahkan ada yang mumpuni,” ujar Cyntha Hariadi. Ia menegaskan bahwa sepuluh cerpen terpilih karya penulis emerging UWRF 2026 menunjukkan kedewasaan dan kepekaan penulis-penulis muda Indonesia ini dalam merespons dunia di sekitar dan dalam diri mereka dengan cara penulisan kreatif masing-masing yang beragam dalam teknik dan rasa.
Bagi Cyntha Hariadi, tema perempuan menonjol tahun ini, dengan kedalaman berlapis oleh penulis dari berbagai tradisi dan gender. Karakter dalam “Perempuan Bawah Langit” karya Nityasa Wijaya (Gianyar) menjadi gelap mata dan dalam kegelapan itu ia baru merasa menjadi manusia seutuhnya meskipun dirinya hancur dalam melawan. Ajen Angelina (Ruteng) dalam “Ungkes dan Mbepet” membongkar cerita rakyat dan memberikannya makna baru demi pilihan kehidupan yang lebih baik meskipun tidak umum. Cerita cinta terlarang dalam latar budaya tradisional dijalin secara apik oleh Carisya Nuramadea (Bogor) dalam “Belajar Menarik Napas”.
Ketiga naskah dari Nityasa, Ajen, dan Carisya menunjukkan pola menarik: semua berakar kuat pada budaya spesifik tetapi melakukan pembongkaran dari dalam. Dengan perlawanan sunyi, reinterpretasi cerita rakyat, dan navigasi identitas queer dalam bayang-bayang sistem gender lokal, mereka tidak terburu-buru melompat ke perlawanan heroik, tetapi menunjukkan bagaimana kuasa tradisi bekerja dengan sangat halus dan menawarkan pilihan-pilihan apa yang mungkin tersedia bagi perempuan dalam memperjuangkan hak untuk mendefinisikan diri sendiri.
Sementara itu, isu kerusakan alam pun digarap dengan kebaruan penceritaan yang lebih subtil, menghasilkan pembacaan yang lebih membangkitkan kesadaran tentang kesatuan manusia dengan alam. Galuh Ginanti (Denpasar) menceritakan “Kersen dan Cerita Sakti” bagai dongeng yang hangat berakhir pahit tak terelakkan seperti hilangnya kepolosan kanak-kanak dalam dunia yang tergerus zaman; sedangkan “Karembong” karya R. Abdul Aziz (Bandung) meninggalkan dengung lembut di telinga dengan menampilkan batu sebagai narator cerita yang puitis. Abdul tampak mengolah musikalitas bahasa dengan serius, dengan rima dalam dan ritme kalimat yang tertata rapi.
Di luar cerpen Galuh dan Abdul, kami melihat munculnya kecenderungan kuat untuk mendekonstruksi sudut pandang antroposentris dalam naskah-naskah yang disertakan dalam seleksi emerging writers. Ada narator atau tokoh utama pesut, sungai, kera, arca, dan lain-lain. Para penulis tidak lagi menempatkan alam sebagai latar atau korban pasif, tetapi sebagai subyek naratif yang setara—dengan kesadaran, ingatan, dan agensi yang unik. Pergeseran dari narasi ekstraktif menuju narasi simbiotik ini semoga bukan hanya terobosan teknik, tetapi juga semacam upaya untuk berdialog dalam percakapan multidisiplin, misalnya dengan filsafat ekologi kontemporer.
Teknik penceritaan realistis dengan latar urban dan semi urban yang membungkus kritik sosial dan budaya secara mulus sekaligus menghibur, terdapat dalam beberapa cerpen lainnya. Pada “Jendil”, Jein Oktaviany (Bandung) menyoroti dinamika kekuatan polisi dan preman di sebuah pasar yang berakibat fatal. Naskah Jein adalah salah satu cerpen dengan plot terbaik yang kami baca. Kisah kerentanan manusia dalam keterasingan kota besar dan ancaman dunia digital lahir dari cerpen “Afrodisiak” karya IRZI (Jakarta) dan “Kedongkolan Rahmat” karya Dhias Nauvaly (Yogyakarta). Keduanya mencerminkan kegelisahan manusia urban yang tak lagi punya pegangan. IRZI sangat piawai mengolah metafor yang menyarankan lapis-lapis makna tentang kehidupan individu di kota metropolitan, kota dengan kepribadian yang terbelah. Sementara itu, Dhias terampil mengelola tensi cerita, pembukaan cerpennya berhasil menjerat pembaca untuk terus mengikuti adegan demi adegan sampai tiba menuju kejutan di akhir kisah.
Selain memberi penekanan pada keunggulan naskah-naskah terpilih sebagai cerpen yang lancar berkisah dan berdaya pukau, Siska Yuanita memberi sorotan khusus pada cerpen-cerpen yang mengangkat fenomena kehidupan dunia digital. “Dari 600-an cerpen yang saya baca, selain tema-tema besar seperti perampasan lahan, penindasan, isu lingkungan, isu gender, sebagian cerita berlatar kontemporer dan urban menampilkan dunia digital seperti ojol dan media sosial sebagai elemen utama. Ini memperlihatkan betapa kehidupan digital sudah demikian jamak sehingga ia telah menjadi sebentuk kebudayaan tersendiri, dengan kekhasan dan problematikanya sendiri. Budaya digital adalah sepotong cermin masyarakat Indonesia yang bahkan melampaui batas geografi,” ujarnya.
Kemudian, tema rantau dan tegangan identitas dituliskan dengan piawai dan menawan dalam “Bulan di Langit Terik” karya Hamran Sunu (Palopo), sedangkan dalam “Perempuan Ular”, Arianto Adipurwanto (Lombok Utara) menggambarkan kekuatan perempuan yang ditakuti, sebagai simbol ketakutan manusia akan liyan, yang tak terpahami dan mengandung teror. Menarik ditilik bagaimana Arianto memberi nama pada tokoh-tokoh kubu liyan, sementara tokoh-tokoh normal dibiarkan tak bernama. Pemberian nama, dalam hal ini, merupakan pilihan politis dan estetis yang memberi dampak besar pada kisah. Sementara itu, cerpen Hamran sangat fasih memainkan alur, bergerak ulang-alik antara ruang tradisi dan ruang modern, antara luka masa silam dan kegelisahan masa kini. Kedua cerpen mereka adalah contoh cerpen dengan tema lokalitas dan tegangan identitas yang berhasil. Dalam bentuknya yang terbaik, dengan spirit dekolonisasi, lokalitas dalam cerpen-cerpen yang kuat tampaknya beralih dari sekadar representasi budaya menuju proyek pemulihan ingatan dan perebutan kembali hak bercerita.
Akhirnya, terima kasih kepada 634 peserta seleksi emerging writers 2026, tanpa kecuali. Selamat kepada para penulis pemula UWRF terpilih. Kami yakin kesepuluh emerging writers ini akan terus bisa berkontribusi dalam memperkaya sastra Indonesia, bahkan menerobos batas-batasnya. Dalam konteks kurasi, menemukan naskah-naskah emerging writers sangatlah berharga. Selain memperkaya khazanah sastra Indonesia dengan variasi tematik dan eksperimen bentuk, naskah-naskah itu seperti mengingatkan kita bahwa sastra Indonesia yang besar akan selalu bersifat multipolar—terdiri dari banyak kutub narasi yang masing-masing berdaulat, yang membuka percakapan satu sama lain, dan bersama-sama membentuk suatu imajinasi kebangsaan yang jauh lebih dalam, organik, dan inklusif.
Dewan Kurator
A. Nabil Wibisana
Siska Yuanita
Cyntha Hariadi